Buaku yang Tertinggal Lapangan sepakbola itu masih seperti dulu. Disudutnya masih tegak berdiri monument kecil. Empat buah jamnya pun masih ada. Sayang “waktunya” telah berhenti. Jarum jamnya tak lagi berdetak. Di depannya, monument perjuangan Bua tetap masih berdiri kokoh.
Tak banyak berubah dengan 28 tahun silam. Demikian halnya dengan SDN 65 Bua tempatku bersekolah dulu. Bangunan dan fasilitasnya pun nyaris sama dengan belasan tahun silam. Disampingnya, balai desanya pun tak berubah. Jika dulu tak ada tulisan dan coretan, kini di berbagai sudutnya terukir jelas coretan yang tak bisa dibilang indah.
Sungai Bua, tempat kami mandi telanjang bahkan menjadi tempat membolos pada jam sekolah, kini banyak berubah. Airnya tak lagi jernih. Luasnya pun hanya beberapa meter. Airnya tak lagi sederas dulu. Keramba ikan yang dulunya berisi ratusan ikan air tawar yang dipelihara di sungai ini pun tak lagi ada. Kalau dulu cokelat dan padi menjadi sumber mata pencaharian masyarakat kampungku, kini tak lagi menjanjikan.
Ironis sebab ku tahu, sebagian besar masyarakat kampungku bergantung pada hasil panennya. Di saat negara dan bangsa ini kekurangan beras hingga harus mengimpornya dari Thailand, Burma dan Malaysia, yang kulihat, ratusan hektar sawah masyarakat kampungku justru disulap menjadi perumahan bahkan sebagian lahannya dipakai membangun bandara. Sementara hektaran kebun kakao juga bagai telur diujung tanduk.
Tak ada lagi ibu dengan bedak tebal di pinggir jalan mengaduk jemuran kakao basahnya. Atau KUD yang dulu menampung kakao para petani. Bahkan puluhan hektar hutan sagu di kampungku nyaris tak tersisa. Semuanya ludes seiring dengan lenyapnya semangat gotong royong dalam kegiatan “mipare”.
Lalu bagaimana sumber pendapatan masyarakatku? Kondisi memaksa mereka beralih pekerjaan, dari petani menjadi pekerja pabrik, merantau atau mereka yang beruntung menjadi PNS. Lalu kemanakah semangat gotong royong itu?. Kini yang tersisa hanya semangat “siapa lo siapa gue” budaya kota besar yang juga menggerus budaya di tanah kelahiranku. Di bidang telekomunikasi, iuran sebesar 150 ribu yang setahun lalu dibayar puluhan kepala keluarga untuk pemasangan jaringan telephone juga tak kunjung kring. Entah apa sebabnya.
Pemekaran Kabupaten Luwu dan menjadikan masyarakat kampungku “sengsara”. Paling tidak untuk ongkos transportasi. Karena semuanya harus diurus ke Belopa, 60 km dari Bua. Inikah filosofi pemekaran yang katanya memperpendek rentan kendali pemerintahan? Delapan belas tahun kutinggalkan tanah kelahiranku, dan kini ia masih seperti dulu, masih tertinggal… Aku sendiri tak meremehkan pembangunan yang dilaksanakan di kampungku.
Delapan belas tahun ku tinggalkan tanah kelahiranku, yang kujumpai hanya empat bangunan fasilitas public yang baru dibangun. Pertama bangunan Puskesmas yang dulunya kecil kini berdiri dengan megahnya, SMAN I Bua yang dibangun diatas lahan yang dulunya hutan sagu, kantor camat Bua yang seingatku dulunya merupakan pasar rakyat dan kantor Polsek yang dibangun diatas bekas sawah.
Ditulis oleh:Sahria
Mengubah atau Random Mac Address Interface Mikrotik Generator
-
Mengubah atau Random Mac Address Interface Mikrotik GeneratorMengubah
alamat MAC suatu antarmuka pada router MikroTik dapat berguna untuk
berbagai alasan s...
1 tahun yang lalu



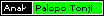













1 komentar:
huff..,
ironis memang..,
Posting Komentar